diam api
Diam itu tidak selalu berarti tak berdaya. Kadang, itu adalah neraka kecil yang dipelihara dengan minyak amarah dan disiram bensin frustrasi. Kau tahu, semacam bom waktu. Jangan bodoh dengan menganggap orang yang memilih diam itu pengecut. Kau tahu apa? Diam itu seni—seni menyusun kehancuran dalam kepala, sembari tersenyum manis pada kebodohan dunia.
Diam itu jebakan, kau mengerti? Di dalamnya ada ribuan ucapan tajam yang ingin merobek tenggorokanmu, tapi aku menahan. Aku memilih diam bukan karena tidak mampu, tetapi karena membiarkan lidah ini berbicara adalah melepaskan binatang liar. Dan binatang itu tak kenal belas kasihan. Aku tak ingin dunia berakhir hari ini hanya karena mulutku mengucapkan apa yang kau pantas dengar.
Kau pikir ini soal kekalahan? Hah, aku memilih diam karena amarahku terlalu besar untuk ditampung oleh obrolan recehmu. Kau akan melihat, suatu saat nanti, diam ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Sebuah badai sunyi yang akan menelan segalanya. Bahkan mungkin kau juga.
"Kau tahu kenapa aku diam?"
Senyum tipis mengukir di wajahku. "Karena kalau aku bicara, kau takkan keluar dari sini hidup-hidup."
Aku mendekat, perlahan, dengan langkah sepelan detak jam dinding. "Diam ini adalah caraku menghitung detik menuju kehancuranmu. Kau lihat aku tenang? Kau salah. Aku tidak tenang. Aku menunggu. Menunggu sampai kepalamu cukup bodoh untuk mendekatkan diri pada pisau di tanganku."
"Oh, jangan takut," aku berbisik dingin, sedingin pisau yang berkilau di bayangan lampu. "Aku tidak akan melukai tubuhmu. Tidak sekarang. Tidak sampai aku puas melihat kau remuk sendiri dengan rasa bersalah yang kubiarkan menelanjangimu pelan-pelan."
Aku tertawa kecil, seperti bisikan angin di malam penuh bintang. "Jadi, mari lanjutkan permainan ini. Kau bicara. Aku diam. Tapi jangan lupa, aku tidak pernah bermain untuk kalah."
Aku memiringkan kepala, menatapnya seperti seorang hakim yang tahu vonisnya sudah pasti. "Kau tahu apa yang menarik dari semua ini?" ucapku pelan, nyaris seperti bisikan maut. "Aku tidak perlu menyentuhmu untuk menghancurkanmu. Diamku sudah cukup. Kau akan membawa kehancuran itu sendiri, menggenggamnya erat seperti kawan lama, sampai akhirnya kau jatuh."
Dia menatapku dengan mata yang mencoba membaca, mencoba memahami. Bodoh. Aku tersenyum samar, seperti bayangan yang bersembunyi di balik malam. "Ingat baik-baik wajah ini, suaraku, diamku. Karena ini yang akan menghantuimu nanti, di tengah malam yang sunyi, ketika kau terbangun dengan napas tersengal dan rasa takut yang tak berwujud."
Aku berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh. "Kau pikir kau menang karena aku diam? Tidak, sayang. Kau hanya diberi waktu untuk menghitung detik sebelum semuanya runtuh."
Angin pengiring menyampaikan pesan sadis dengan cara yang paling romantis, dia menanyaimu sekali lagi "Apakah kepergianku adalah tangga juara yang layak kau rayakan? Tidak bro, tidak sama sekali. Kau hanya sedang membangun akhir yang paling dramatis dari rencanamu untuk bunuh diri."
Sebelum menghilang sepenuhnya dari pandangannya, aku berhenti sejenak, hanya untuk menambahkan dengan suara yang dingin, nyaris tanpa emosi, "Dan ketika itu terjadi, jangan salahkan aku. Salahmu sendiri karena berpikir aku tak mampu."
Langkahku menjauh, meninggalkan keheningan yang terasa berat, seperti napas terakhir seseorang sebelum menyerah. Di belakangku, aku tahu dia merasakan apa yang ingin kutinggalkan: bukan rasa takut pada ancaman, tapi rasa takut pada ketiadaan. Karena aku bukan hanya ancaman. Aku adalah kehampaan yang akan menyelimutinya dengan kehangatanrasa takut yang abadi di setiap tidur dan waktu kau menjelangnya. Adakah penawar dari keabadian rasa itu? Mungkin kau bertanya, Ada!! satu penawar mati tanpa tawar hati atau wajah iba. Kau akan sembuh berangsur waktu ketika kau terjaga dan mengawali setiap pagi dengan tangis masokismu. Itu akan berjalan beberapa hari, mungkin tahun berganti sampai kau kembali dan tau diri, tau siapa dirimu sendiri.
Pomalaa, 20241231
duiCOsta_hatihati

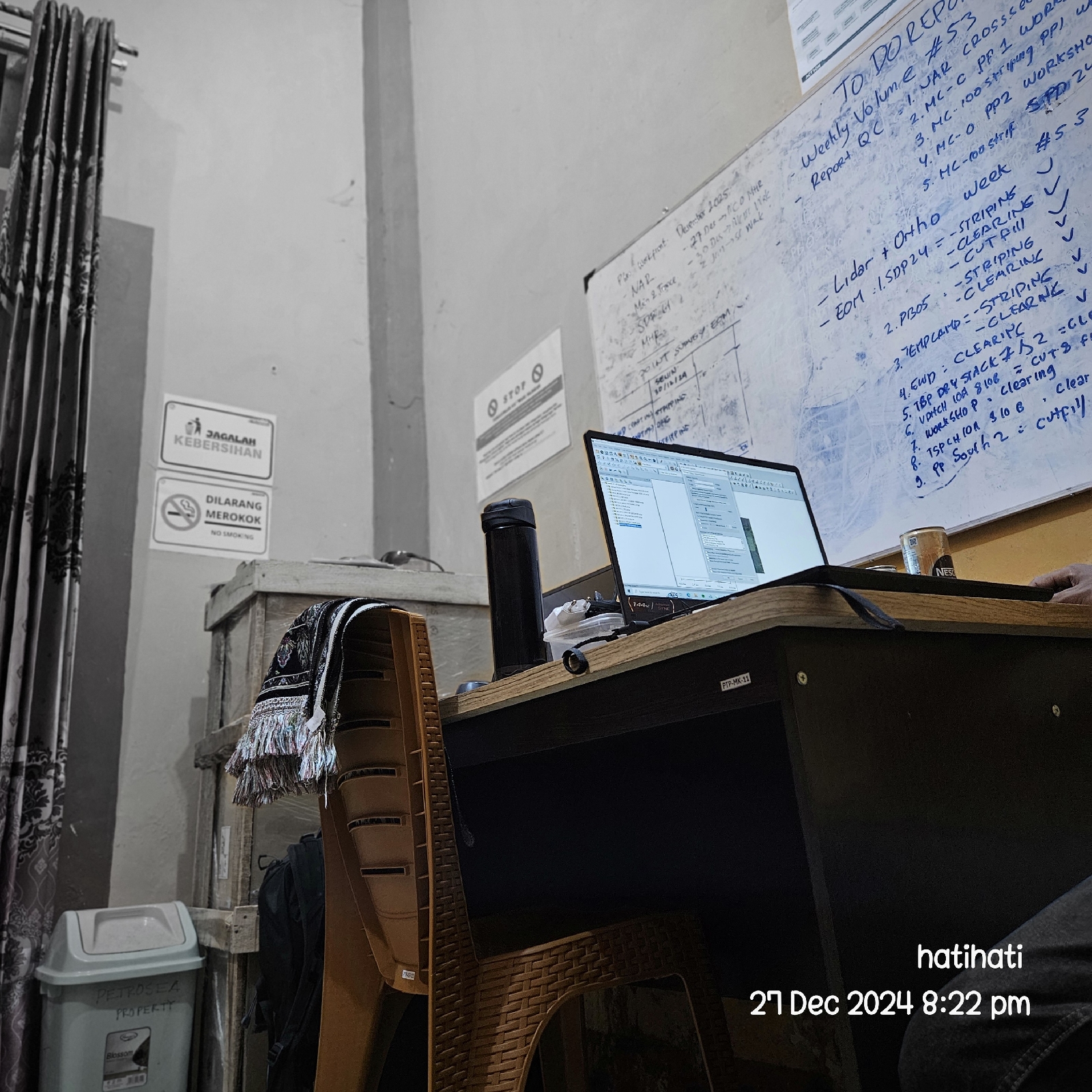


Comments
Post a Comment